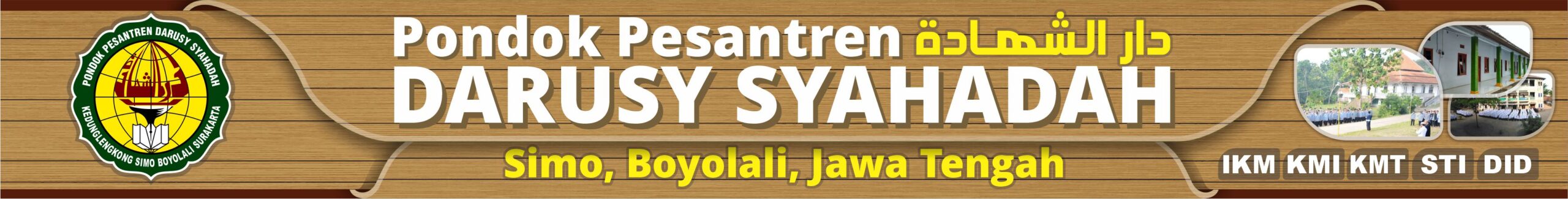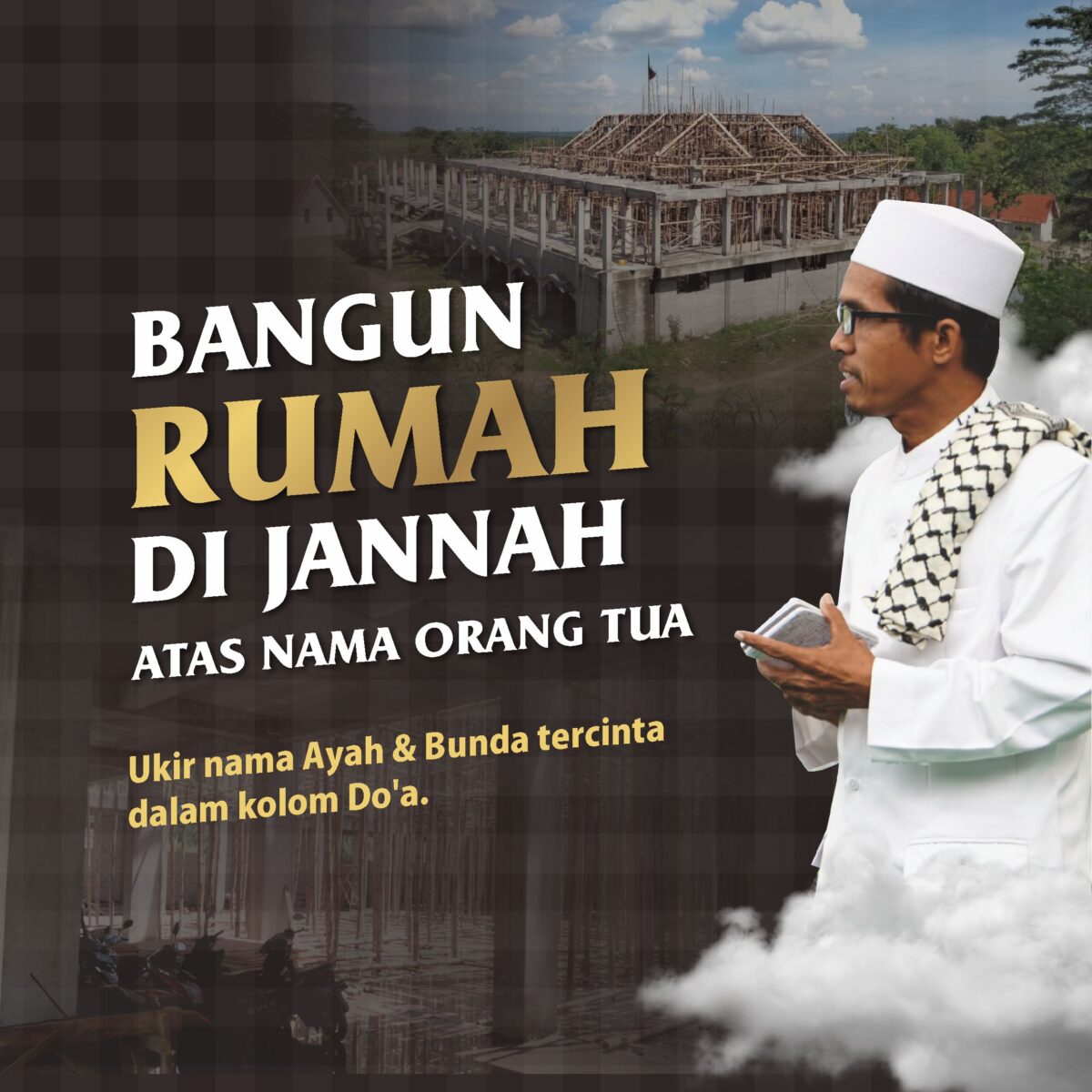Daftar Isi
Oleh : Santri Darsya
Pendahuluan
Ketika berbicara tentang Sumpah Pemuda 1928, banyak orang langsung teringat pada organisasi pemuda sekuler seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, atau Jong Ambon. Namun, jika menelusuri lebih dalam, tampak bahwa kaum santri, ulama, dan pesantren juga memiliki kontribusi besar dalam membangun kesadaran nasional yang melandasi lahirnya Sumpah Pemuda.
Di balik lantunan doa dan kajian kitab kuning, pesantren sejatinya menanamkan nilai cinta tanah air yang menjadi inti nasionalisme Indonesia. Para ulama dan santri bukan hanya penonton, melainkan aktor ideologis dan moral yang menyiapkan fondasi kebangsaan.
Tulisan ini berusaha merekonstruksi peran tersebut secara ilmiah—bagaimana santri, ulama, dan pesantren menjadi bagian penting dalam lahirnya semangat persatuan bangsa.
Latar Historis: Pesantren, Ulama, dan Nasionalisme Islam sebelum 1928
Awal abad ke-20 menjadi masa kebangkitan kesadaran Islam dan nasionalisme di kalangan pesantren. Salah satu gagasan kunci yang hidup kala itu adalah “Hubbul Wathan Minal Iman” — cinta tanah air sebagian dari iman — yang disuarakan oleh Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy’ari.
Ungkapan tersebut bukan sekadar semboyan, melainkan penegasan bahwa kecintaan terhadap tanah air sejalan dengan ajaran agama. Dalam tulisan Lukman Hakim (Jurnal UIN SGD Bandung, 2019) disebutkan:
“Historically, Islam was actually very nationalistic, particularly in the Dutch colonial times.”
Artinya, jauh sebelum Sumpah Pemuda, nasionalisme religius sudah tumbuh di dunia pesantren sebagai bagian dari iman dan perjuangan.
Selain itu, munculnya organisasi pemuda Islam seperti Jong Islamieten Bond (JIB) pada 1 Januari 1925 di Batavia menjadi bukti konkret peran santri dan pelajar Islam dalam gerakan kebangsaan. Dalam buku Jong Islamieten Bond: Pergerakan Pemuda Islam 1925–1942 (Abdurrahman & Darmansyah, Kemdikbud), disebutkan bahwa JIB bertujuan “menjembatani kesenjangan kultural politik antara intelektual dan rakyat.”
Dengan kata lain, pesantren dan kalangan santri telah menginternalisasi nasionalisme jauh sebelum jargon “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa” dikumandangkan.
Keterlibatan Santri dan Ulama dalam Gerakan Pemuda Menuju Sumpah Pemuda
JIB: Wadah Gerakan Pemuda Islam
JIB menjadi tonggak penting karena berhasil melampaui semangat kedaerahan. Menurut Fadillah & Subakti (Journal of Islamic Studies and Humanities, 2023), JIB menghadirkan “warna baru dalam pergerakan pemuda Indonesia yang bersifat lintas daerah sekaligus berbasis nilai Islam.”
Dengan hadirnya JIB, pemuda Islam menjadi bagian aktif dalam proses menuju Sumpah Pemuda, sekaligus menunjukkan bahwa persatuan tidak harus menanggalkan identitas religius.
Ulama dan Pesantren sebagai Sumber Moral dan Ideologis
Nilai “hubbul wathan” menjadi jembatan antara iman dan nasionalisme. KH. Hasyim Asy’ari menanamkan pemahaman bahwa membela bangsa adalah bagian dari ibadah. NU Online mencatat bahwa beliau menciptakan “ramuan penyatu antara cinta agama dan cinta bangsa.”
Penelitian Syafira Dewi Anjani (Jurnal JEJAK UNJA, 2021) menambahkan bahwa “kaum santri memberikan dukungan moral dan spiritual terhadap perjuangan bangsa.”
Dengan demikian, pesantren menjadi sumber energi moral bagi gerakan nasional.
Koneksi dengan Kongres Pemuda 1928
Walaupun tidak tercatat secara eksplisit dalam daftar peserta resmi Kongres Pemuda II, jaringan dan gagasan JIB yang telah aktif sejak 1925 menunjukkan bahwa arus pemikiran Islam dan santri turut membentuk atmosfer kebangsaan yang berpuncak pada ikrar Sumpah Pemuda.
Nilai Persatuan dalam Sumpah Pemuda dan Refleksi Pesantren
Sumpah Pemuda mengikrarkan tiga hal: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketiganya sejatinya telah lama hidup dalam nilai-nilai pesantren — ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan).
Dalam Jurnal Pendidikan Islam (Hakim, 2019) ditegaskan bahwa pendidikan Islam telah menjadi basis pembentukan nasionalisme, di mana “ajaran Islam mendorong umat untuk mencintai tanah air sebagai amanah Tuhan.”
Pesantren, dengan tradisi bahasa Arab, Jawa, Sunda, dan Melayu, tetap menghargai bahasa daerah tetapi juga mendorong penggunaan Bahasa Indonesia sebagai alat persatuan. Artinya, nilai Sumpah Pemuda sejalan dengan spirit Islam yang mengajarkan harmoni dalam perbedaan.
Setelah Sumpah Pemuda: Pesantren sebagai Garda Perjuangan
Peran santri tidak berhenti pada tataran ide. Pasca 1928, mereka tampil di garis depan perjuangan kemerdekaan. Semangat “hubbul wathan minal iman” menjadi napas perlawanan, seperti tampak pada Resolusi Jihad 1945 yang melahirkan peristiwa heroik 10 November di Surabaya.
Menurut Anjani (JEJAK UNJA, 2021), “santri berperan dalam mobilisasi moral dan massa selama perjuangan kemerdekaan.”
Hal ini menegaskan bahwa nasionalisme santri tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga praksis — diwujudkan dalam perjuangan nyata.
Analisis dan Implikasi
Analisis Historis
Sumpah Pemuda sering diidentikkan dengan gerakan intelektual sekuler, padahal organisasi pemuda Islam telah lebih dahulu membangun jembatan persatuan lintas daerah.
Gagasan-gagasan keagamaan seperti “hubbul wathan” menjadi akar bagi nasionalisme Indonesia yang religius, bukan imitasi dari Barat.
Pesantren menyediakan kerangka moral, spiritual, dan kultural bagi lahirnya nasionalisme yang berkarakter keislaman.
Implikasi bagi Pendidikan Pesantren
Penulisan sejarah nasional perlu merevisi paradigma lama dengan memasukkan kontribusi santri dan ulama sebagai pelaku sejarah bangsa.
Bagi pesantren hari ini, nilai-nilai Sumpah Pemuda dapat menjadi refleksi untuk membentuk santri nasionalis-religius, yang mencintai bangsa karena iman.
Kesimpulan
Kaum santri, ulama, dan pesantren adalah bagian integral dari sejarah Sumpah Pemuda.
Mereka hadir bukan sekadar penonton, tetapi sebagai penggagas nilai, penjaga moral, dan penggerak ideologis.
- Nasionalisme religius telah tumbuh di pesantren sebelum 1928.
- JIB membuktikan peran pemuda Islam dalam gerakan persatuan nasional.
- Nilai-nilai pesantren seperti ukhuwah dan cinta tanah air sejalan dengan isi Sumpah Pemuda.
- Setelah 1928, santri melanjutkan perjuangan hingga kemerdekaan.
Dengan demikian, membaca Sumpah Pemuda melalui kacamata pesantren membuat kita memahami bahwa persatuan bangsa tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari rahim spiritual kaum santri yang mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman.
Daftar Pustaka
- Abdurrahman, Momon & Darmansyah, et al. Jong Islamieten Bond: Pergerakan Pemuda Islam 1925–1942. Museum Sumpah Pemuda/Kemdikbud, Jakarta.
- Fadillah, Alif Fikri & Subakti, Ganjar Eka. “Dari Jong Java ke Jong Islamieten Bond: Pergeseran Identitas dan Politik Pemuda Islam Indonesia (1924–1942).” Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 9 No. 1, 2023. DOI:10.21580/jish.v9i1.21613.
- Hakim, Lukman. “Nasionalisme dalam Pendidikan Islam.” Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 27 No. 2, 2019. DOI:10.15575/jpi.v27i2.506.
- Anjani, Syafira Dewi. “Melacak Akar Historis Perjuangan Bangsa Indonesia dan Kiprah Kaum Santri dalam Lahirnya NKRI.” JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah, Vol. 3 No. 2, 2021. DOI:10.22437/jejak.v3i2.24860.
- “Hubbul Wathan Perspektif Gagasan dan Perjuangan K.H. Mas Mansur.” JAWI (Jurnal Al-Wasilah), Vol. 4 No. 2, 2022. DOI:10.24042/jw.v4i2.10781.